Pertama kali aku bertemu dengan London, aku tahu kalau London akan mengubah hidupku suatu saat nanti.
London adalah laki-laki yang menyenangkan. Selalu tersenyum, menjadi sumber semangat untuk teman-temannya, dan memandang dunia dengan perspektifnya sendiri.
Cara London memandang langit sama sepertiku. Cara kami menerjemahkan sebuah bahasa menjadi rasa juga sama. Kami juga gemar bermain kata, menjadikannya sebuah lagu yang tak akan pernah dinyanyikan.
London adalah lelaki yang impulsif. Tak ada kata "tabu" dalam kamusnya, dan dia percaya bahwa apa yang telah dia lakukan selama ini tidak pernah salah.
Kami sempat dipisahkan oleh waktu. Cukup lama, hingga aku lupa akan eksistensinya. Dan beberapa waktu lalu, London kembali membawa berita yang sebenarnya tidak begitu aku harapkan.
"It's been ten years," kata London saat dia duduk di teras rumahku. "Dan aku menaruh dendam pada orang-orang yang pernah ada di hidupmu waktu itu."
Jam menunjukkan pukul 02.34. London terus mengoceh tentang perasaannya. London yang kecewa, London yang hidup dalam kebencian, dan cintanya padaku. Tentu saja, apa yang dia ungkapkan berubah menjadi angin ribut di dalam kepalaku.
Sekitar pukul 04.21, London memutuskan untuk pulang. Wajahnya muram, tapi dia memaksakan diri untuk tersenyum saat mata kami beradu. "Aku tidak mengharapkan apa-apa darimu. Tapi, izinkan aku untuk tenggelam dalam pikiranmu yang tak pernah bisa aku baca itu."
Aku merasa dijebak oleh London, El. Tapi, aku senang, karena aku tahu isi pikirannya sekarang.
Kami tidak butuh waktu lama untuk beradaptasi. Toh, kami sudah saling mengenal cukup lama. Kami, 'kan, juga menganut paham yang sama.
Hingga suatu hari, London memutuskan untuk hengkang dari apa yang sudah dia mulai. Tidak, dia tidak menyerah. Tapi, dia sadar telah mengambil langkah yang salah, dan dia telah melukai seseorang. Orang itu aku, El.
"Aku akan pergi jauh dari kamu untuk waktu yang sangat lama," katanya. "Aku tidak akan beri tahu kamu kapan aku akan pergi. Aku akan bilang satu hari sebelumnya."
London bicara seakan tak punya beban, El. Dia tersenyum saat mengatakan hal itu padaku. Tapi aku tidak bodoh, El. Hatinya menjerit, dan aku mendengarnya.
Tak ada yang berubah sejak London mengucapkan kalimat itu. London datang dan pergi begitu saja, dan aku tidak mempermasalahkannya.
Suatu malam, aku bertanya padanya apakah dia sedang berusaha untuk membuat memori denganku. Kau tahu dia jawab apa, El?
"Aku tidak suka dengan pertanyaan itu. Aku sudah punya banyak memori tentang kamu. Hanya saja, memori yang menyedihkan jauh lebih banyak. Jadi, aku ingin membuatnya setara-- memori yang menyenangkan, dan yang buruk."
Beberapa hari setelahnya, kami bicara lagi. Bukan tentang kami, tapi tentang perspektif kami masing-masing yang sebenarnya tidak ada bedanya. Percakapan kami pun mengarah pada hal yang tidak ingin kami bahas. Kepergiannya.
"Ya, aku menghindar," katanya. Aku tidak menjawab. Memang, aku tidak pernah memberikan jawaban saat London bicara tentang "kami".
London menarik napas panjang dan membakar rokok yang berada di tangannya sejak lima menit yang lalu. Asap putih tebal keluar dari mulutnya dengan perlahan, dan ia berdecak,
"Aku tidak mau hidup di sana."
London menunjuk dadaku. Telunjuknya pun beralih ke kepalaku.
"Tapi di sana."
London adalah laki-laki yang istimewa, El. Dia bisa menghancurkan aku kapan saja. Bahkan, dia bisa menyeretku untuk masuk ke dalam deritanya.
Kami tinggal menunggu waktu. Setiap aku bangun dari tidurku, aku selalu dihantui akan kapan sebenarnya dia pergi.
Baru-baru ini, London datang ke rumahku. Dia membawakanku sepotong besar kue cokelat, Iced Green Tea Latte dari Starbucks, dan sebuah buku catatan.
"Aku dan kamu mungkin sudah mati rasa. Tapi, aku telah memutuskan untuk berbagi beban dengan kamu. Aku tidak peduli apakah kamu menerima hal itu atau tidak."
"Waktu kita sempit. Kamu harus memperbolehkan aku untuk menyakitimu sekali lagi."
Dan air mataku menetes saat London menepuk dahiku dengan tersenyum.
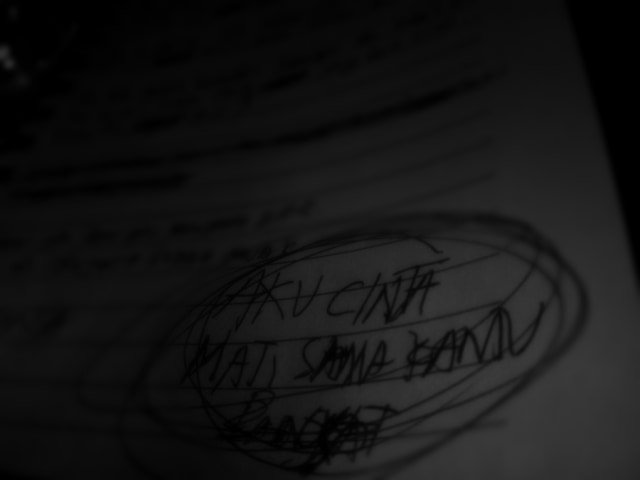

No comments:
Post a Comment