Sunday, August 30, 2020
Sadino's Monologue #10
Sadino's Monologue #9
Pertama kali aku bertemu dengan London, aku tahu kalau London akan mengubah hidupku suatu saat nanti.
London adalah laki-laki yang menyenangkan. Selalu tersenyum, menjadi sumber semangat untuk teman-temannya, dan memandang dunia dengan perspektifnya sendiri.
Cara London memandang langit sama sepertiku. Cara kami menerjemahkan sebuah bahasa menjadi rasa juga sama. Kami juga gemar bermain kata, menjadikannya sebuah lagu yang tak akan pernah dinyanyikan.
London adalah lelaki yang impulsif. Tak ada kata "tabu" dalam kamusnya, dan dia percaya bahwa apa yang telah dia lakukan selama ini tidak pernah salah.
Kami sempat dipisahkan oleh waktu. Cukup lama, hingga aku lupa akan eksistensinya. Dan beberapa waktu lalu, London kembali membawa berita yang sebenarnya tidak begitu aku harapkan.
"It's been ten years," kata London saat dia duduk di teras rumahku. "Dan aku menaruh dendam pada orang-orang yang pernah ada di hidupmu waktu itu."
Jam menunjukkan pukul 02.34. London terus mengoceh tentang perasaannya. London yang kecewa, London yang hidup dalam kebencian, dan cintanya padaku. Tentu saja, apa yang dia ungkapkan berubah menjadi angin ribut di dalam kepalaku.
Sekitar pukul 04.21, London memutuskan untuk pulang. Wajahnya muram, tapi dia memaksakan diri untuk tersenyum saat mata kami beradu. "Aku tidak mengharapkan apa-apa darimu. Tapi, izinkan aku untuk tenggelam dalam pikiranmu yang tak pernah bisa aku baca itu."
Aku merasa dijebak oleh London, El. Tapi, aku senang, karena aku tahu isi pikirannya sekarang.
Kami tidak butuh waktu lama untuk beradaptasi. Toh, kami sudah saling mengenal cukup lama. Kami, 'kan, juga menganut paham yang sama.
Hingga suatu hari, London memutuskan untuk hengkang dari apa yang sudah dia mulai. Tidak, dia tidak menyerah. Tapi, dia sadar telah mengambil langkah yang salah, dan dia telah melukai seseorang. Orang itu aku, El.
"Aku akan pergi jauh dari kamu untuk waktu yang sangat lama," katanya. "Aku tidak akan beri tahu kamu kapan aku akan pergi. Aku akan bilang satu hari sebelumnya."
London bicara seakan tak punya beban, El. Dia tersenyum saat mengatakan hal itu padaku. Tapi aku tidak bodoh, El. Hatinya menjerit, dan aku mendengarnya.
Tak ada yang berubah sejak London mengucapkan kalimat itu. London datang dan pergi begitu saja, dan aku tidak mempermasalahkannya.
Suatu malam, aku bertanya padanya apakah dia sedang berusaha untuk membuat memori denganku. Kau tahu dia jawab apa, El?
"Aku tidak suka dengan pertanyaan itu. Aku sudah punya banyak memori tentang kamu. Hanya saja, memori yang menyedihkan jauh lebih banyak. Jadi, aku ingin membuatnya setara-- memori yang menyenangkan, dan yang buruk."
Beberapa hari setelahnya, kami bicara lagi. Bukan tentang kami, tapi tentang perspektif kami masing-masing yang sebenarnya tidak ada bedanya. Percakapan kami pun mengarah pada hal yang tidak ingin kami bahas. Kepergiannya.
"Ya, aku menghindar," katanya. Aku tidak menjawab. Memang, aku tidak pernah memberikan jawaban saat London bicara tentang "kami".
London menarik napas panjang dan membakar rokok yang berada di tangannya sejak lima menit yang lalu. Asap putih tebal keluar dari mulutnya dengan perlahan, dan ia berdecak,
"Aku tidak mau hidup di sana."
London menunjuk dadaku. Telunjuknya pun beralih ke kepalaku.
"Tapi di sana."
London adalah laki-laki yang istimewa, El. Dia bisa menghancurkan aku kapan saja. Bahkan, dia bisa menyeretku untuk masuk ke dalam deritanya.
Kami tinggal menunggu waktu. Setiap aku bangun dari tidurku, aku selalu dihantui akan kapan sebenarnya dia pergi.
Baru-baru ini, London datang ke rumahku. Dia membawakanku sepotong besar kue cokelat, Iced Green Tea Latte dari Starbucks, dan sebuah buku catatan.
"Aku dan kamu mungkin sudah mati rasa. Tapi, aku telah memutuskan untuk berbagi beban dengan kamu. Aku tidak peduli apakah kamu menerima hal itu atau tidak."
"Waktu kita sempit. Kamu harus memperbolehkan aku untuk menyakitimu sekali lagi."
Dan air mataku menetes saat London menepuk dahiku dengan tersenyum.
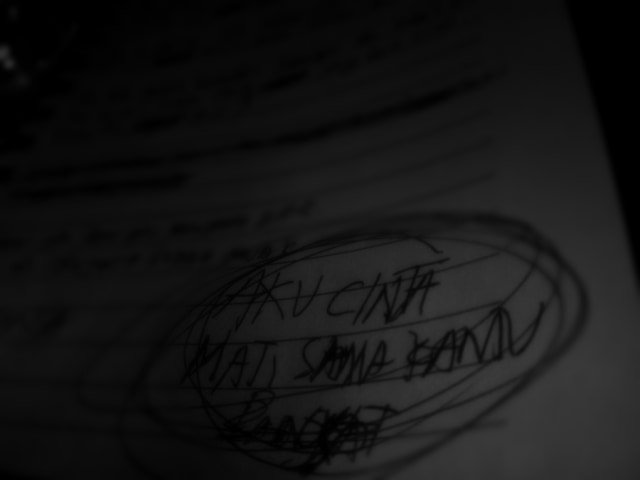
Sadino's Monologue #8
Manusia dan tabula rasa adalah sebuah kolaborasi yang konkret. Seorang bayi lahir membawa rasa, dan logika menyusul beberapa tahun kemudian. Rasa dan logika berada di dalam frekuensi yang sama. Apa sulitnya?
Cinta itu terbagi dengan sendirinya, El. Kamu merasakannya, bukan? Tapi kenapa hal ini begitu rumit? Kenapa aku gagal untuk melakukan sinkronisasi?
Dia, misalnya. Dia memilih untuk bersembunyi di balik egonya, membiarkan tubuhnya hanyut dalam kekalutan. Mulutnya ingin bicara, tapi rasa takut menguasai pikirannya.
Dia memperlakukan dirinya dengan hati sekeras baja. Alasannya, timbal balik dalam kehidupan. Aku pikir, manusia hanya berpindah tempat, El. Manusia hanya bertukar posisi untuk mendapatkan pengalaman. Serupa, tapi tak sama.
Apa sulitnya untuk jujur terhadap diri sendiri? Ya, ini masalah terbesarku, El. Dia juga. Apa salahnya meminta untuk dikasihi? Apa salahnya menyentuh tanpa mengharapkan imbalan?
Teruslah memuja kemenangan atas diri sendiri. Karena hal itu tidak masuk akal, dan manusia menyukainya. Kadang, menjadi sosok yang idealis itu memang diperlukan. Tapi, sampai kapan?
Modalnya hanya percaya, El. Manusia tidak perlu mengganti kerugian yang dibuat oleh orang lain. Tapi, kenapa manusia--dan aku tentunya-- memilih untuk bergantung dengan itu?
Mungkin seorang Elohim tidak pernah merasakan peliknya sebuah kasus yang mengatasnamakan jiwa. Apa sulitnya untuk bertanya? Membuka aib yang menjadi problematik, 'kan, sah-sah saja.
Mungkin manusia harus berhenti bercermin. Mungkin manusia harus berhenti menggugat satu sama lain. Aku memilih untuk menggantung harapanku, El. Aku muak dengan alibi tentang solidaritas. Haruskah aku merajah dia agar rahangnya bekerja?
Aku ingin mendengar dia mendesah, El. Aku ingin dia menyebut namaku. Aku ingin batin kami menyatu, membentuk kisah yang baru, tanpa campur tangan imajinasi ataupun realitas.
Sayang, dia memilih untuk bungkam, El. Dia memilih untuk menjahit lukanya sendiri saat tangan kami saling menggenggam. Dia ingin menyikapi hubungan ini dengan bijak. Tapi, hal itu berubah menjadi misi bunuh diri.
Aku rasa, dia cukup pintar untuk berubah, El. Hanya saja, kenyataan merenggut kehidupannya dan membalutnya dengan kecemasan. Dan, aku tak punya otoritas untuk itu.
Sadino's Monologue #7
Manusia itu cemburu karena serakah, dan keserakahan itu muncul saat sekumpulan manusia berlomba untuk mendapatkan keamanan. Mereka saling mencakar, menjambak, hingga satu orang terpilih sebagai pemenang. Dalam kata lain, pembunuh.
Tidak, aku tidak cemburu, El. Hanya saja, orang-orang ini tak punya otak. Mimpi mereka terlalu tinggi, padahal pola pikir mereka tak pernah berpindah tempat.
Aku sering mendengar mereka bergumam. Mereka berusaha memberikan solusi, padahal mereka hanya mengeluh dengan mengemas "solusi" yang tidak solutif.
Untuk apa mereka membuang waktu untuk berbagi derita? Lebih baik, orang-orang ini mati saja. Kenapa mereka berpikir diri mereka mampu mendidik orang lain? Padahal, mereka tidak pernah mengakui akan kehadiran seorang guru.
Aku pernah memandangi diriku di cermin selama lebih dari tiga jam. Aku mengasihani diriku yang berpeluh demi bahagiaku. Serumit inikah perjuangan manusia untuk menjadi sosok yang "normal"?
Rasanya, aku ingin mengutuk manusia yang tak punya watak. Aku benci manusia yang terus membodohi dirinya sendiri.
Manusia itu harus tahu diri. Manusia adalah konseptor terhebat di muka Bumi. Tapi, kenapa manusia kerap memilih hal-hal di luar kompetensi?
Mungkin bagi mereka, hal itu menyenangkan. Aku akui, hal itu memang menyenangkan. Dan cara mereka untuk meraih eksistensi lewat pola pikir yang pendek adalah tayangan favoritku dalam beberapa tahun terakhir.
Manusia bebas untuk memilih. Kenapa mempersulit diri sendiri dengan sebuah abstraksi?
Sadino's Monologue #6
Aku seperti sedang mendengar sebuah himne. Samar-samar, melodi akan sebuah musik yang sendu mengalun dengan perlahan, membelai telinga, hingga bulu kuduk berdiri.
Apa ini, El? Aku sudah menutup telingaku, dan himne ini tetap terdengar. Entah ini himne atau bukan, tapi suara-suara yang terdengar seperti sedang memuja sesuatu.
Sebentar, El. Aku bisa mendengar denyut nadiku sekarang. Aku bisa merasakannya, El. Darah yang mengalir dengan perlahan, udara yang bergulat di dalam paru-paru, otot-otot yang lemas, pupil mata yang perlahan mengecil.
Nyanyian itu semakin terdengar. Suara seorang perempuan dan laki-laki saling bersahutan, membuat sebuah lingkaran yang tak kasat mata di antara mereka. Gelombang suara mereka bergaung hingga ke cakrawala, membentuk sebuah garis lengkung yang membelah langit.
Aku melihat diriku sendiri, El. Aku yang rapuh, aku yang nanar memandang diriku. Tubuhku terlihat memar di berbagai bagian, El. Ujung bibirku berdarah, kedua mataku lebam.
Aku bergeming. Aku mulai cemas. Tak ada angin yang menerpa wajahku. Pasir seakan berbisik, membawa pesan yang tak mampu kubaca. Aku dan diriku masih saling menatap. Dan nyanyian itu semakin keras.
Inikah dogma yang selama ini kubenci?
Inikah aku yang terbiasa dengan kehadiran sebuah stigma?
Apakah sesungguhnya perempuan ini, perempuan yang berdiri dengan anggun tanpa alas kaki, benar-benar hidup?
Kami berdua kontras, El. Aku bisa melihat mata lembayungnya dengan jelas. Dunia terbakar di sana.
Wajahku perih, El. Pipiku seperti tergores sesuatu. Dan sekarang, darah mengalir pelan hingga ke daguku, mengingatkanku pada hangatnya dekapan seorang ibu.
Ini ulahmu, El. Aku menyalahkanmu. Bukan karena tidak ada lagi yang bisa disalahkan, tapi karena duniaku ada di sana, dalam genggamanmu.
Cukup, El. Ini menyakitkan. Aku harap, aku mengerti maksud dari perjalanan ini. Aku dan kamu akan jadi satu. Kita akan meronta bersama, saling memohon, dan mengampuni.
Nyanyian itu mendadak berhenti. Duniaku kembali sunyi, dan aku melihatmu sekarang. Itu aku, El, itu suaraku. Dan itu suaramu, El. Ini caraku untuk bernyanyi, dan kau membantu dengan mengasihi.
Wednesday, August 12, 2020
Sadino's Monologue #5
Sadino's Monologue #4
Tuesday, August 11, 2020
Sadino's Monologue #3
Sadino's Monologue #2
Aku muak, El. Dunia ini penuh dengan keburukan. Manusia saling menghakimi satu sama lain, saling menggugat, berkelahi lewat suara.
Aku sedang menggapai sesuatu, El. Demi menghapus kebosanan, tentunya, dan itu tidak mudah. Aku harus berpikir, melihat bayanganku sendiri, dan dikejar waktu.
Dan orang ini datang, mematikan semangatku, merobek luka, dan mengambil kebahagiaanku. Padahal, dia adalah sosok yang acuh tak acuh, kerap memandang dunia dengan mempermudah pola pikirnya, dan gemar berbagi beban yang tidak ingin aku pikul.
Sebentar. Aku bingung. Apakah aku harus menggunakan 'aku' atau 'kami' dalam hal ini? Vox populi? Oh, oke, 'aku' lebih tepat, karena ini egoku.
Aku heran, El. Dulu, aku selalu memujinya. Di mataku, dia adalah orang yang cerdas dan bijak. Aku merasa dia peduli padaku.
Dan dunia berputar. Pikiranku digempur dengan kebencian. Mendadak, si tolol bersabda, "Jangan seenaknya sendiri. Pikirkan orang lain, jangan buat aku marah."
Seharusnya, dia bertanya, "Ada apa denganmu?" atau, "Apa yang salah denganku?" Seharusnya, dia sadar bahwa apa yang aku lakukan selama ini adalah sebuah penolakan-- aku tidak ingin menjadi orang yang kotor dari segi pikiran.
Andai aku bisa mengumpat setiap menit, tapi itu melelahkan. Andai otaknya bekerja lebih keras. Andai saja, dia mau mengakui dosa-dosanya. Aku mungkin tidak akan mengampuni, dan kebodohannya mungkin bisa memberikan jalan keluar untuk sosoknya yang dia agung-agungkan itu.
Entah apa yang berkecamuk di dalam pikirannya, tapi pintaku, dengarkan isi kepala mereka. Tawarkan bantuan untuk mereka yang sekiranya, membutuhkan sebuah solusi. Memang, ini kerja kerasku yang tak perlu diapresiasi. Tapi, jangan merendah untuk menjadi semakin rendah. Karena aku pikir, dia sudah salah langkah.
Dia berlaku semaunya, membedakan seseorang dengan orang lain yang duduk penuh tekanan. Aku pikir, dengan belajar menghargai sesama, matanya akan terbuka dengan mudah. Jika tidak bisa, apakah mungkin aku harus menghancurkan tengkoraknya hingga darahnya mengalir turun bak air mata?
Aku tahu dia mampu mendengar sumpah serapah yang diteriakkan padanya. Bodohnya, dia menolak untuk mendengar. Bodohnya lagi, dia tidak peduli. Aku khawatir jika suatu saat nanti, dia akan tunduk pada suara yang membawa fakta akan siapa dirinya yang sebenarnya.
Apa, El? Biarkan saja?
Awalnya memang begitu sampai detik ini tiba. Aku hanya tidak sanggup berhadapan dengan pendusta. Lagi-lagi, dia memaksaku untuk tidak mengabaikannya, memberiku tekanan yang seharusnya dia pikul, hingga kesabaranku berada di tapal batas.
Aku akan melakukan sesuatu, El. Aku akan membuatnya marah. Aku akan membuatnya kecewa. Silakan, anggap saja aku balas dendam. Karena sesungguhnya, manusia tidak berhadapan dengan karma, melainkan hanya bertukar tempat untuk mengerti yang mana prioritas, dan mana yang bukan. Sekarang, dia sedang berjalan untuk berdiri di tempat yang aku beri jiwa.
Panggil aku sang pengkhianat, dan aku akan memperkenalkannya pada dunia yang lebih waras dari isi kepalanya.
Sadino's Monologue #1
Aku dan Bayangan Tentang Jonghyun
Kim Jonghyun. Salah satu anggota grup musik K-Pop bernama SHINee. Usianya masih 27 tahun. Di usianya yang masih sangat muda, Jonghyun memilih untuk menghilangkan penatnya dengan caranya sendiri. Untuk selama-lamanya.
Jonghyun adalah seorang idola. Sembilan tahun ia berkarier bersama SHINee, hingga namanya diagungkan oleh para perempuan dari berbagai belahan dunia.
Sekilas, Jonghyun memiliki apa yang orang-orang inginkan; ketenaran, skill, cinta, harta, dan kebahagiaan. Ingat, sekilas.
Tidak hanya Jonghyun, tapi aku bisa melihat proses di balik pencapaiannya untuk mendapatkan semua itu. Darah dan keringat bercampur menjadi satu, mengalir dari ujung kepala hingga ke ujung kakinya, di saat otot-otot tubuhnya dipaksa bekerja untuk mendapatkan gelar sebagai seorang idola.
Aku mengerti bahwa jalan ini telah dipilih oleh Jonghyun. Dengan niat dan keikhlasan hati, Jonghyun memilih untuk menantang diri dan nyalinya, karena baginya, manusia tak punya batasan untuk apa yang mereka inginkan.
Aku paham, Jonghyun pasti mengerti maksud dari kalimat 'no pain, no gain' dan 'hard work pays off'. Dia terus menggenggam makna dari kedua kalimat itu. Dia menyemayamkannya di dalam dadanya. Jonghyun tahu apa yang dia mau.
Hingga akhirnya, SHINee melakukan debutnya pada Mei 2008 lewat EP berjudul "Replay". Dunia mendadak gila, karena semua penikmat musik K-Pop seakan berkiblat kepada SHINee.
Album-album SHINee pun menghiasi industri musik K-Pop sekaligus menjadi penanda bahwa pamor SHINee seakan tak akan pernah turun dari singgasananya di puncak bukit. SM Entertainment, agensi tempat SHINee bernaung, pun melihat peluang lain untuk hal ini; masing-masing anggota SHINee adalah 'dagangan' yang menggiurkan.
Hal itu terbukti, karena Onew, Taemin, Key, Minho, dan juga Jonghyun ternyata berpotensi untuk menjadi lebih dari sekadar idola. Masing-masing dari mereka memiliki talenta, dan berbagai kegiatan yang mampu mendongkrak popularitas mereka pun mulai diperhitungkan.
Pada Januari 2015, Jonghyun merilis EP perdananya yang bertajuk "Base". Lagi-lagi, bisnis yang tengah dijalani SM Entertainment kembali menuai keuntungan. "Base" laku keras di pasaran hingga membawa pulang penghargaan Disk Bonsang dari ajang Golden Disk Awards 2016.
Jika pada saat itu aku berada di posisi Jonghyun, tentu aku akan merasa puas. Karierku sebagai solois sukses. Aku memenangi sebuah penghargaan dan seluruh mata tertuju padaku. Karyaku diakui para penikmat K-Pop, dan kerja kerasku membuahkan hasil.
Tak puas, Jonghyun merilis album penuh pertamanya di tahun 2016, "She Is". Karyanya yang satu ini kembali menuai kesuksesan, dan Jonghyun kembali menundukkan industri K-Pop dengan musiknya.
Mendadak, aku teringat akan Michael Jackson. Idolaku yang satu ini selalu menelurkan karya yang membuat orang-orang berdecak kagum. Bahkan, begitu mudahnya Michael melahirkan lagu-lagu yang membuat orang tak pernah berhenti untuk menyanyikannya, seakan dia memang dilahirkan untuk menjadi seorang bintang.
Tapi, Michael kesepian. Dia kerap mengungkap keadaannya yang sebenarnya di balik cahaya panggung yang menyorotnya tanpa henti. Dia kesepian. Dia lelah. Tapi, itu semua adalah jalan yang dia ambil, dan dia menerima segala konsekuensinya.
Aku tidak bisa membayangkan bagaimana seorang Michael Jackson yang terlihat selalu menebar senyum kepada semua orang yang menyapanya, hidup dalam kesendirian. Meski dia hidup bergelimang harta dan perempuan tergila-gila padanya, dia tetap merasa kesepian. Pada akhirnya, musik adalah sahabat terbaiknya. Sebuah pelipur lara, dan bentuk bahagianya.
Ini yang mungkin dirasakan oleh Jonghyun. Musik adalah hidupnya, dan bekerja keras untuk menjadi idola yang lebih baik adalah tujuan hidupnya. Musik adalah bukti bahwa dirinya berbakat. Musik adalah bentuk cintanya pada dirinya sendiri.
Tapi, Jonghyun sendirian. Saat tak ada musik yang terdengar, Jonghyun mungkin merasa bahwa dia sedang berada di sebuah ruangan kecil tanpa cahaya. Mungkin, dia menolak untuk menerima kenyataan bahwa tanpa musik, jantungnya akan berhenti berdetak.
Jonghyun terus memacu dirinya. Masih berpegang teguh dengan kalimat 'manusia hidup tanpa batas', Jonghyun memaksa tubuhnya untuk bergerak, untuk berkeringat, untuk berdarah. Semua demi kecintaannya pada musik.
Hingga akhirnya, realitas memeluknya dengan paksa, membuka kedua matanya, dan menyadarkan bahwa paru-parunya tak sanggup lagi bekerja. Dia lelah, dan secara perlahan, dia merasa seperti menghilang. Apa yang sebenarnya dia cari? Apa itu bahagia? Apa yang sedang aku lakukan?
Konsepsi individu tentang dirinya sendiri pun perlahan muncul. Egonya itu menusuk tubuhnya dengan perlahan, membangunkan sebuah rasa yang selama ini dia pendam; amarah dan kekecewaan. Lagi-lagi, Jonghyun hilang di dalam pikirannya sendiri. Inikah yang aku inginkan?
Tekanan demi tekanan menyerang Jonghyun tanpa henti. Dia dipaksa untuk kembali melewati batas oleh egonya, tapi mentalnya tak sanggup menyebrang. Jonghyun berkutat dengan dirinya; menyalahkan dunia dan mimpinya yang dulu menjadi semangatnya.
Jonghyun berusaha melarikan diri dari kenyataan. Namun, rasa tidak pernah puas yang ada dalam setiap diri manusia menariknya ke belakang. Jonghyun dipermainkan oleh dirinya sendiri. Jonghyun dikhianati oleh pencapaiannya selama ini.
Andai aku bisa meraihnya saat itu, mungkin aku bisa membantu Jonghyun untuk mengembalikan sosoknya yang dulu. Aku rasa, hal ini juga dirasakan oleh mereka yang mencintai Jonghyun. Mereka yang ingin menyelamatkan Jonghyun dari bahaya yang telah mengincarnya sejak dulu. Mereka yang ingin memeluk Jonghyun untuk memberinya ketenangan.
Tapi, haram hukumnya bagi seorang idola untuk terlihat lemah dan sedih di hadapan orang-orang yang mencintainya. Jonghyun terus memberikan kekuatannya pada orang-orang di sekitarnya, padahal dia sendiri butuh pertolongan.
Konsep 'bahagia saja duluan, aku belakangan' pun diusung Jonghyun. Semua demi cinta yang menghujaninya selama ini. Ratusan ribu dukungan yang diterima Jonghyun tidak akan bisa dia balas dengan apapun. Maka dari itu, Jonghyun memilih untuk berkubang dengan ketakutannya demi membahagiakan orang lain.
Terlalu lama. Terlalu menyakitkan. Terlalu menyedihkan.
"Aku kesakitan," kata Jonghyun. "Berhenti menyakitiku."
"Aku lelah," bisiknya pada dirinya sendiri. "Aku sudah tak ingin lagi berlari mengejar sesuatu yang fana."
"Relakan aku," pikirnya dalam hati. "Biarkan aku tidur. Sebentar saja."
Dalam hitungan menit, gas monoksida memenuhi paru-parunya. Sengal, sesak.
"Aku yakin aku bisa," kalimat tersebut terus berputar di pikiran Jonghyun. "Aku mencintai hidupku, sebagaimana kamu mencintai hidupmu."
Aku akan terlahir kembali, untuk bahagiamu.
Dan seluruh media di Korea Selatan memberitakan bahwa Jonghyun telah berhenti bernapas saat dia sedang dalam perjalan ke rumah sakit. Sang bintang tak lagi bersinar. Dia memilih untuk hidup dalam kebahagiaan yang ia buat sendiri.
Sejenak, aku merasa seperti melihat bayangan Jonghyun. Jonghyun yang sedang menari--tidak, tidak-- Jonghyun yang sedang menari dalam kerasahannya. Jonghyun yang sedang bermimpi, mempersilakan matahari pagi menyinari wajahnya. Jonghyun yang kuat, Jonghyun yang hebat.
Jonghyun yang meminta agar keputusannya ini dihargai.
괜찮아요 ... Jonghyun.
Dariku, yang Mencintaimu Hanya di Kala Senja
Jakarta, 12 Januari 2018
Januariku tahun ini tidak akan sama seperti Januariku tahun lalu. Karena aku akan pergi, jauh dari kamu. Aku tahu ini klise, tapi alasanku tetap sama-- aku tidak mau maju karena aku hanya akan mempersulit keadaan.
Apa yang aku hadapi sekarang ini bukanlah suatu hal yang baru. Apa yang aku dan kamu lakukan hanya akan menjadi sebuah cerita yang repetitif. Mungkin, kita akan saling mengekang, memberi tekanan pada satu sama lain. Ya, represif.
Hingga detik ini, aku masih menyesali apa yang aku perbuat dulu. Kenapa catatanmu tidak aku baca? Kenapa pada saat itu aku berpikir bahwa buku catatan kecil bersampul hitam itu hanyalah catatan kosong seorang lelaki?
Sampai akhirnya, kamu memberiku catatan berhargamu itu--untuk kedua kalinya-- pada akhir tahun lalu. Segala bentuk coretan dan torehan lukamu menghiasi setiap halaman catatan kesayanganmu itu.
London, Ini tentang aku. Hingga halaman terakhir, namaku tertera di sana.
Sekarang, izinkan aku untuk memaki diriku sendiri. Aku menolak untuk bicara padamu karena aku hanya akan menciptakan sebuah ilusi. Aku akan simpan kalimat itu baik-baik, dan aku akan membakarnya saat kita sudah jadi musuh.
Aku pikir ini adil. Aku tak mau menambah masalah. Kehadiranmu di depanku saja sudah menjadi masalah besar. Apapun yang kau lakukan, aku yang merasakan sakitnya.
Kamu akan pergi. Dan aku akan jatuh membentur tanah, bertekut lutut seraya memandangmu menjauh, dan menghilang dengan perlahan.
Kamu tidak akan menoleh ke belakang. Jika hal itu terjadi, berarti doaku selama beberapa minggu terakhir ini dijabah. Jika tidak, aku akan membisu, dan belajar untuk lebih menerima arti dari sebuah perpisahan.
Ini berat. Aku tahu, kamu juga merasakan hal yang sama. Kita hanya terlalu banyak membuang waktu, berharap mimpi akan datang merengkuh ekspektasi.
Kita pergi untuk saling melukai. Dan aku bisa terima itu. Mungkin, aku bisa mengobati keangkuhan yang selama ini hidup di dalam darahku. Mungkin, kepergianmu akan menjadi salah satu momen favoritku untuk dikenang.
Mungkin, aku tidak mencintai kamu seperti kamu mencintai aku. Mungkin, aku mencintai kamu hanya di kala senja. Senja yang meronta dari kegelapan, melukis langit lembayung untuk menyambut malam yang dingin.
Mungkin, aku mencintai kamu di saat kamu tak ada. Wujudmu akan mendominasi pikiranku, menjadikan aku seorang perempuan yang tak lekang oleh waktu.
Kenapa hanya di kala senja? Karena senja itu indah, dan matahari terlihat berpendar dari kejauhan. Dan senja itu, menenangkan.
Dan apa hubungannya dengan kamu? Karena kamu adalah fenomena yang jarang sekali aku temui. Dan senja merepresentasikan warna yang membalutmu selama ini.
Akan datang hari yang memaksamu untuk terus berlari. Senjaku bernyanyi, merintih memanggil nama yang sudah tak asing lagi. Senjaku bermusik, dan aku akan menemani hingga keresahan mengambil alih.
Jika kamu meninggalkan aku di kala senja, aku akan berdiri di kaki langit,
dan mencintaimu dari sana.










